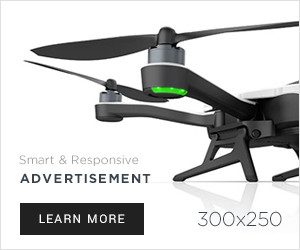Tarshadigital.com (Floroda) – Tepat hari ini, Kamis, 19 Februari 2026, perhatian dunia kembali tertuju pada Pad 39B di Kennedy Space Center. Para insinyur NASA sedang melakukan upaya kedua uji coba pengisian bahan bakar (wet dress rehearsal) untuk roket Space Launch System (SLS) yang akan membawa misi Artemis II. Langkah ini terpaksa dilakukan setelah uji coba awal Februari lalu gagal total akibat masalah klasik yang terus menghantui badan antariksa tersebut: kebocoran hidrogen cair.
Jika semuanya berjalan mulus, minggu ini seharusnya menjadi perayaan kembalinya empat astronaut dari orbit Bulan. Namun, realitanya Reid Wiseman dan kru lainnya masih tertahan di Bumi, dengan jadwal peluncuran yang kini tergeser ke Maret 2026. Mengapa NASA seolah “keras kepala” tetap menggunakan hidrogen meski reputasinya buruk karena sering memicu pembatalan misi?
Efisiensi Tanpa Tanding di Ruang Hampa
Alasan utama kesetiaan NASA terletak pada hukum fisika. Hidrogen cair (LH2) adalah elemen paling ringan di alam semesta, namun memiliki kepadatan energi yang luar biasa saat dipasangkan dengan oksigen cair. Dalam dunia roket, terdapat ukuran yang disebut Specific Impulse (Isp), semacam indikator efisiensi bahan bakar.
Hidrogen memiliki nilai Isp tertinggi dibandingkan opsi bahan bakar kimia lainnya. Artinya, hidrogen mampu memberikan “dorongan” atau gaya angkat yang jauh lebih besar per kilogram bahan bakar dibandingkan bahan bakar tradisional seperti minyak tanah (kerosene) atau bahkan metana yang digunakan SpaceX. Bagi roket raksasa seperti SLS yang harus membawa kapsul Orion seberat 26 ton menuju Bulan, efisiensi ini sangat krusial untuk menjaga bobot roket tetap masuk akal saat lepas landas.
Molekul Terkecil yang Sulit Dijinakkan
Namun, keunggulan fisik hidrogen adalah juga kelemahannya. Sebagai molekul terkecil, hidrogen cair adalah “ahli meloloskan diri”. Ia mampu merembes keluar melalui celah mikroskopis pada sambungan pipa atau segel yang tidak akan bisa dilewati oleh bahan bakar lain.
Kondisi ini diperparah oleh suhu penyimpanannya yang ekstrem, yakni minus 252 derajat Celsius (minus 423 derajat Fahrenheit). Pada suhu sedingin itu, logam pada roket menyusut dan menjadi rapuh. Perubahan bentuk material inilah yang seringkali merusak kerapatan sambungan (umibilical) antara menara peluncuran dan roket, memicu kebocoran yang dideteksi oleh sensor sensitif NASA, seperti yang terjadi pada awal Februari 2026 lalu.
Warisan Politik dan Mandat Kongres
Selain faktor teknis, ada aspek kebijakan yang jarang dibahas. Pembangunan roket SLS diatur oleh undang-undang di Amerika Serikat yang mewajibkan NASA menggunakan kembali perangkat keras dan infrastruktur dari era Space Shuttle (1981-2011). Mesin RS-25 yang menjadi jantung SLS adalah mesin yang sama yang digunakan pada pesawat ulang-alik, yang memang dirancang khusus untuk membakar hidrogen.
Mengganti bahan bakar berarti harus merancang ulang mesin dari nol, sebuah proses yang akan memakan waktu dekade dan biaya miliaran dolar tambahan. Dengan demikian, NASA terjebak dalam dilema antara efisiensi teknis yang tinggi dan ketergantungan pada teknologi warisan yang “rewel”.
Rekor Keamanan yang Teruji
Meskipun sering menyebabkan penundaan yang membuat publik frustrasi, NASA menekankan bahwa protokol keamanan mereka bekerja dengan baik. Sensor kebocoran yang sangat sensitif justru menjadi bukti bahwa sistem pengawasan mereka mampu mencegah bencana sebelum roket meninggalkan landasan.
Hingga saat ini, para insinyur terus melakukan modifikasi pada material segel dan prosedur pengisian bahan bakar yang lebih lambat agar material memiliki waktu untuk beradaptasi dengan suhu dingin ekstrem. Bagi NASA, hidrogen cair mungkin adalah mitra yang sulit diatur, namun tetap menjadi tiket terbaik bagi manusia untuk kembali menjejakkan kaki di permukaan Bulan dalam misi-misi Artemis mendatang.